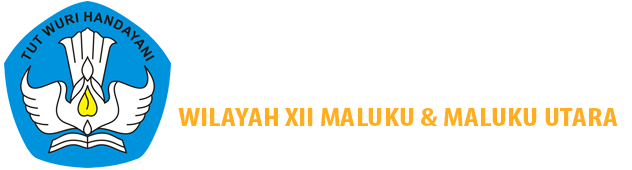Minimnya Paten di Indonesia
Hampir seperempat abad sejak Undang-Undang Paten pertama hadir di Indonesia tahun 1989, tetapi permohonan hak paten masih terbilang minim. Data Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, permohonan paten dalam negeri tahun 2011 berjumlah 820 permohonan. Jumlah itu sedikit meningkat dari tahun 2009 dan 2010 sebanyak 684 dan 795 permohonan.
Bandingkan jumlah paten dalam negeri itu dengan paten dari luar negeri yang jauh lebih masif. ”Gempuran” paten dari luar negeri yang didaftarkan di Indonesia terus meningkat. Tahun 2009 ada 4.145 permohonan paten asing, tahun berikutnya meningkat menjadi 5.035 permohonan, tahun 2011 (5.432), dan tahun 2012 (6.212). Hal itu mengindikasikan bahwa pasar domestik Indonesia saat ini, khususnya terkait produk-produk teknologi, praktis ”dijajah” pihak asing.
Di kancah internasional, Indonesia juga tergolong ”miskin” paten internasional. Paten internasional adalah hak paten yang didaftarkan ke negara lain.
Tahun 2010, Indonesia hanya memiliki 15 paten internasional, sedangkan Malaysia dan Singapura masing-masing mendaftarkan 302 paten dan 637 paten. Jepang? Lebih dahsyat lagi. Tahun 2010, Jepang memperoleh 32.156 paten internasional.
Sejauh ini, Indonesia juga telah meratifikasi perjanjian internasional tentang paten yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang bisa memberikan sejumlah kemudahan dalam proses pengakuan paten yang ditemukan anak negeri. Sejumlah paten yang dikenal dan diterima baik di dunia internasional di antaranya konstruksi fondasi ”cakar ayam” temuan Prof Sedijatmo dan teknik memutar lengan jalan layang ”Sosrobahu” temuan Tjokorda Raka Sukawati.
Memang, selepas kedua nama paten tersebut, relatif sedikit temuan paten dari dalam negeri yang dikenal publik secara luas. Sejumlah persoalan ditengarai menjadi penyebab rendahnya jumlah pemohon paten di Indonesia. Di sisi lain, ada kondisi kesadaran masyarakat Indonesia untuk mematenkan karya yang terbilang rendah. Padahal, serpihan inovasi sebenarnya terserak di berbagai pelosok negeri.
Mengacu pada kategori paten yang ada, pengajuan paten tak harus merupakan teknologi tinggi yang rumit dan canggih. Ada pula kategori paten sederhana yang lebih bersifat menemukan kemudahan proses, yang sebenarnya banyak dijalankan di masyarakat. Dalam diskusi tentang paten, terungkap pula ada indikasi kultural di mana sebagian penemu di Indonesia justru tak terlalu peduli dengan dampak komersial dan hukum dari hak paten.
Jumlah peneliti yang masih relatif sedikit dan anggaran penelitian yang terbatas di sejumlah lembaga menjerat sejumlah langkah inovasi anak negeri. Data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), jumlah peneliti saat ini ”hanya” sekitar 8.000 orang, sedangkan pengajar di lembaga perguruan tinggi negeri dan swasta sekitar 160.000 orang. Angka ini terbilang kecil jika dibandingkan dengan total jumlah penduduk Indonesia yang tercatat 238 juta jiwa.
Persentase anggaran penelitian pun terbilang minim. Tercatat hanya sekitar 0,08 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Jumlah itu masih jauh dari angka ideal yang disarankan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa- Bangsa (UNESCO), yakni sebesar 2 persen dari PDB.
Kendala prosedural
Persoalan lain yang menghadang kelancaran dalam inovasi teknologi dan pematenan adalah soal-soal teknis prosedural. Lama waktu pengurusan paten hingga memperoleh sertifikat paten di Indonesia dalam praktiknya bisa mencapai 5-8 tahun, terutama akibat proses-proses verifikasi ilmiah. Itu jauh lebih lama dibandingkan dengan proses pengajuan paten di Amerika Serikat, Jepang, China, dan Singapura yang rata-rata menyelesaikan paten dalam waktu 2-3 tahun.
Biaya pengurusan paten juga relatif mahal, total Rp 6 juta lebih dalam kurun lima tahun. Angka itu bisa menjadi Rp 76 juta untuk kurun 20 tahun pemeliharaan paten. Biaya muncul sebagai konsekuensi pencatatan dan verifikasi paten oleh negara.
Biaya itu jelas memberatkan bagi peneliti, apalagi jika paten yang didaftarkan ternyata tak memiliki sisi komersial, alias semata memenuhi syarat kepangkatan dalam dunia birokrasi. Bandingkan biaya paten ini dengan biaya pengurusan merek yang hanya Rp 600.000 per merek.
Lihat pula sisi kurangnya penghargaan bagi inventor. Dari paten yang berhasil dikomersialkan dan digunakan khalayak, keuntungannya tidak masuk ke inventor, tetapi menjadi penerimaan negara bukan pajak institusi, baik perguruan tinggi maupun lembaga lain. Cara itu jelas tidak membuat peneliti termotivasi untuk kreatif karena tidak ada insentif yang bisa didapat.
Hal ini terkait fakta bahwa mayoritas pemohon paten dalam negeri adalah lembaga riset, baik yang berasal dari perguruan tinggi maupun lembaga penelitian pemerintah. Sementara paten yang diajukan pihak swasta atau industri relatif kecil. Sebagai contoh, lembaga yang banyak memohonkan paten hingga tahun 2010 adalah Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan 158 paten, diikuti Kementerian Pertanian 127 paten, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 106 paten, Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) 86 paten, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dengan 53 paten.
Penetapan paten
Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Paten diberikan untuk jangka 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. Setelah jangka waktu itu selesai, invensi menjadi milik publik. Siapa pun bebas menggunakan penemuan itu untuk dimanfaatkan.
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) merupakan lembaga terbanyak yang membukukan hak paten atas hasil temuannya. Hingga tahun 2012, capaian lembaga itu tercatat 296 paten. Dari jumlah tersebut, 55 persen di antaranya masih berstatus paten terdaftar dalam proses, sedangkan yang sudah tersertifikasi baru 24 paten.
Sementara dari pihak swasta, antara lain PT Martina Berto Tbk yang mengajukan permohonan 36 paten, 8 paten dikabulkan dan sisanya masih dalam proses.
Secara historis, peraturan perundangan bidang paten di Indonesia telah ada sejak tahun 1910 saat pemerintahan kolonial Belanda mengundangkan UU Paten. Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Netherlands East-Indies telah menjadi anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888 dan anggota Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works sejak tahun 1914.
Pada zaman pendudukan Jepang, semua peraturan perundangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku.
Saat bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, UU Paten tidak berlaku karena dianggap bertentangan dengan Pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam UU Paten peninggalan Belanda, permohonan paten dapat diajukan di kantor paten yang berada di Batavia (sekarang Jakarta), tetapi pemeriksaan atas permohonan paten tersebut harus dilakukan di Octrooiraad yang berada di negeri Belanda.
Meski UU Paten disahkan pada tahun 1989, paten baru berlaku efektif di Indonesia tahun 1991. Pengesahan tersebut mengakhiri perdebatan panjang tentang pentingnya sistem paten dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia. Dalam pertimbangan UU Paten 1989 disebutkan, perangkat hukum di bidang paten diperlukan untuk memberi perlindungan hukum dan mewujudkan suatu iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuan teknologi.
Bagaimanapun, paten adalah kebutuhan sangat penting bagi bangsa Indonesia yang sedang dalam sejumlah proses pembangunan. Lebih penting lagi, inovasi-inovasi yang dipatenkan bisa diproduksi massal untuk dimanfaatkan publik. (DWI ERIANTO/Litbang Kompas)
Sumber: Kompas Cetak
HKI untuk Meningkatkan Daya Saing
Memiliki daya pikir, rasa, dan karsa setiap manusia berpotensi menciptakan karya intelektual. Kreasinya tertuang dalam bentuk beragam karya cipta, mulai dari seni budaya hingga desain dan rancang bangun teknologi. Semua itu dipandang sebagai aset kekayaan individual yang dilindungi hukum, karena bernilai ekonomi hingga mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya.
Saat ini, kekayaan intelektual itu dikelompokkan dalam delapan rezim perlindungan hukum, yaitu hak cipta, paten, merek, indikasi geografis, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman. Di antara delapan rezim itu, patenlah yang selalu dikedepankan banyak negara di dunia karena dianggap memiliki dampak terbesar bagi peningkatan daya saing bangsa.
Paten, yang merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada inventor atas hasil temuannya berupa proses dan produk teknologi, memang memiliki posisi berbeda dibandingkan tujuh rezim lainnya. Sebab, pada paten tersirat teknologi atas suatu invensi yang sulit penguasaannya.
Ini menjadi kekuatan negara maju, yang memiliki sarana— berupa dana dan fasilitas riset memadai untuk mendorong terciptanya invensi. Sementara itu, negara berkembang seperti Indonesia, karena berbagai kendala, terbatas dalam perolehan paten.
Tidak mengherankan bila selama ini paten terbanyak dimiliki penemu dari negara-negara maju. Menurut data Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ada sekitar 34.000 paten terdaftar. Hampir 95 persen merupakan paten asing.
Berbagai kendala
Berdasarkan data lembaga paten asing, misalnya United States Patent and Trademark Office (USPTO), pada 2010 paten dari Indonesia hanya enam, sedangkan dari Jepang mencapai 44.811. Sangat tak sebanding. Minimnya perolehan paten oleh bangsa Indonesia antara lain karena ketidakmampuan peneliti memenuhi kebutuhan industri, ketiadaan insentif riset hingga pendaftaran paten dan perlindungannya di lembaga HKI, serta tidak adanya mekanisme pembiayaan dan komersialisasi paten.
Dari jumlah paten domestik yang kecil itu pun nyaris tidak ada yang dibeli industri sehingga tidak ada pemasukan bagi penemu dan lembaga riset tempatnya bekerja. Sebaliknya, memelihara paten agar tetap terlindungi selama 20 tahun justru menguras dana sangat besar. Dalam kondisi seperti itu, memiliki paten justru menimbulkan kerugian secara finansial dan menjadi beban bagi lembaga riset.
Data Ditjen HKI menunjukkan, dari 7.490 paten yang perlindungannya dibatalkan demi hukum (BDH) ada 79 paten milik lembaga dan individu di dalam negeri. Meski sedikit jumlahnya, untuk mempertahankannya perlu biaya pemeliharaan miliaran rupiah. Menghadapi masalah itu, pemilik paten perlu mempertimbangkan keberlanjutan pemilikan hak patennya agar tidak menanggung kerugian lebih besar lagi. Apabila paten memang tidak berpotensi ekonomis hingga tidak diminati industri alias ”tidur” dalam waktu sekian lama, sebaiknya paten dilepaskan saja menjadi domain publik.
Sebagian besar paten asing yang dibiarkan hingga BDH diyakini tak lagi memiliki prospek kemanfaatan dan kebaruan lagi. Pendaftaran paten asing yang tak berprospek ekonomi itu boleh jadi bertujuan sekadar mengangkat citra negara di mata dunia sebagai bangsa yang mampu menguasai teknologi dan inovasi.
Sesungguhnya, di manakah kekuatan terbesar daya saing negara maju dalam bidang HKI? Untuk memenangi persaingan di bidang industri dan perdagangan produk dan jasa, rezim yang lebih banyak dipilih adalah rahasia dagang. Rezim ini melindungi kekayaan intelektual mereka dari upaya peniruan oleh pihak pesaing sehingga mereka dapat tetap unggul. Pada rezim HKI tersebut, informasi yang dilindungi kerahasiaannya meliputi metode produksi, metode pengolahan, dan metode penjualan. Rahasia dagang memproteksi informasi itu tanpa batas waktu. Beda dengan paten selama 20 tahun.
Keunggulan komparatif
Melihat berbagai kendala yang membelenggu para penemu di Indonesia dan begitu jauhnya kesenjangan perolehan paten saat ini, tampaknya sangat sulit, bahkan tak mungkin, bagi mereka untuk mengatasi ketertinggalan dari para penemu di negara maju. Paten domestik memang tidak dapat diabaikan dan tetap perlu diupayakan peningkatannya karena menjadi salah satu indikator indeks daya saing bangsa.
Namun, Indonesia masih memiliki ”senjata” lain untuk menaikkan daya saing berbasis HKI. Dalam hal ini, Indonesia justru harus lebih memperhatikan rezim HKI yang memiliki keunggulan komparatif, yaitu kekayaan seni budaya dan sumber daya hayati yang dimilikinya. Maka, pilihan mestinya jatuh pada indikasi geografis dan perlindungan varietas tanaman. Mengapa demikian? Karena pada dua rezim itulah Indonesia memiliki kekayaan intelektual yang terbesar.
Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu produk. Faktor lingkungan geografis, termasuk faktor manusia, dapat memberikan ciri dan kualitas tertentu pada produk yang dihasilkan. Selain perlindungan indikasi geografis dikenal pula indikasi asal dan jaminan keistimewaan tradisional. Ketentuan ini menetapkan hanya produk tertentu yang boleh menggunakan nama tempat asal pembuatannya. Oleh karena itu dapat melindungi kekayaan tradisional dan alam Indonesia.
Adapun Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) merupakan hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pemulia tanaman atau pemegang PVT untuk melakukan perbanyakan tanaman melalui benih atau jaringan biakan dan bahan panen, seperti bunga, buah, dan daun dalam jangka waktu tertentu.
Pemanfaatan indikasi geografis dan perlindungan varietas tanaman ini mestinya dapat meningkatkan kesejahteraan petani, para perajin, dan masyarakat di Indonesia. Sebab, produk yang memiliki indikasi geografis sangat beragam dihasilkan daerah-daerah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.
Namun, rezim HKI itu ternyata belum banyak mendapat perhatian publik. Ditjen HKI hanya mencatat 19 indikasi geografis terdaftar, misalnya untuk produk kopi arabika yang berasal dari Kintamani, Gayo, Flores-Bajawa, dan Kalosi-Enrekang. Indikasi geografis yang didaftar terakhir adalah ubi cilembu Sumedang.
Pada saat bangsa Indonesia mengabaikan kekayaan tradisional dan alamnya, bangsa lain justru gencar memburu dan menyerobot. Kasus akuisisi yang muncul antara lain reog Ponorogo. Di Belanda pun muncul produk bernama Mandailing Coffee. Sementara itu di bidang obat dan makanan; tempe, buah mengkudu, dan berbagai jenis jamu juga telah didaftarkan atas nama asing. Perburuan keragaman hayati di Indonesia juga dilakukan para peneliti asing dengan berbagai cara, baik secara legal maupun ilegal dengan mencurinya.
Untuk itu, dalam era pasar bebas di kawasan ASEAN pada 2015, Indonesia perlu segera mengeluarkan peraturan dan mekanisme perlindungan kekayaan intelektualnya sehingga dapat memberi kesejahteraan sebesar-besarnya bagi warganya.
Sumber: Kompas Cetak